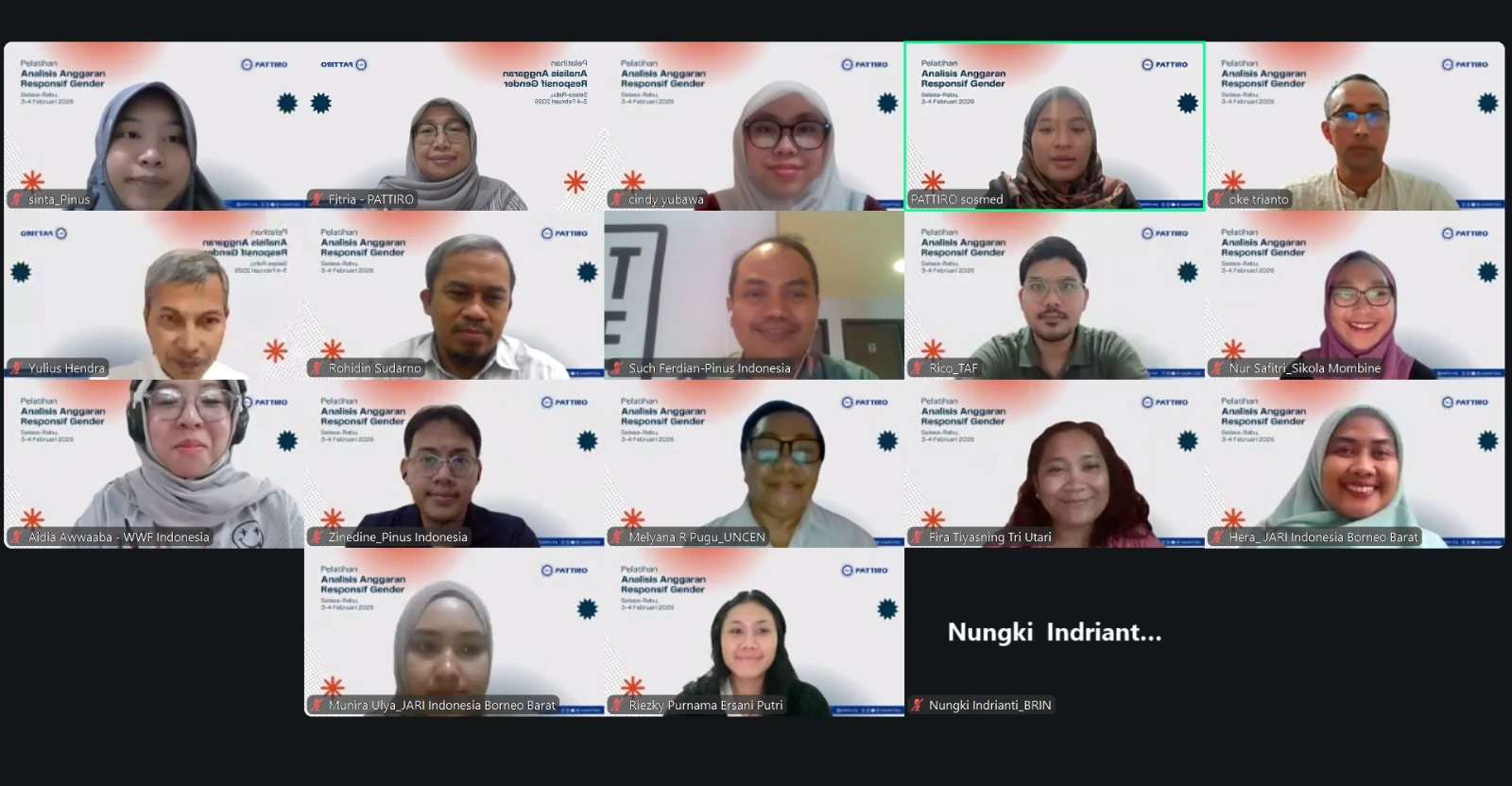Bulan September tahun 2013, Kota Surakarta tengah berupaya menggodok kebijakan baru dalam rangka menuju sebuah Kota Inklusi. Inklusi merupakan sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang semakin terbuka. Hal ini berarti bahwa adanya keterbukaan dan keramahan bagi semua, saling menghargai dan mengikutsertakan perbedaan karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.
Bulan September tahun 2013, Kota Surakarta tengah berupaya menggodok kebijakan baru dalam rangka menuju sebuah Kota Inklusi. Inklusi merupakan sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang semakin terbuka. Hal ini berarti bahwa adanya keterbukaan dan keramahan bagi semua, saling menghargai dan mengikutsertakan perbedaan karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.
Agenda setting pemerintah Kota Surakarta mengkerucut pada persoalan pendidikan inklusif. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pasal 3 ayat 2 Permendiknas ini juga menggolongkan siapa saja yang disebutkan memiliki keleluasaan dalam hal ini ada 10 kategori yakni; tunanetra; tunarungu; tunawicara; tunagrahita; tunadaksa; tunalaras; berkesulitan belajar; lamban belajar; autis; memiliki gangguan motorik; menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; memiliki kelainan lainnya; dan tunaganda.
Konsep pendidikan inklusi sendiri memiliki ruh untuk menjadi pemecah masalah adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan kita, terutama pada anak-anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, mindset kita masih terfokus bahwa pendidikan inklusif ditujukan bagi anak-anak disabilitas. Hal yang belum termaktub dalam Undang-Undang No 70 Tahun 2009 dan Perda Pendidikan Inklusif di daerah lainnya adalah terlewatkannya pemenuhan hak bagi anak korban kekerasan seksual berbasis gender. Secara harfiah mereka juga menjadi bagian dari kelompok berkebutuhan khusus.
Dapat kita ingat mengenai kasus yang menimpa anak perempuan korban kekerasan, baik itu di area publik maupun kekerasan dalam pacaran (KDP). Di Depok misalnya pada tahun 2012 kasus penculikan dan pemerkosaan yang dialami oleh salah seorang siswi SMP di Kota Depok mencuat ke permukaan. Di tengah usia anak-anaknya, Ia harus mengalami pengalaman kekerasan berbasis gender. Masyarakat kita belum mampu digolongan sebagai masyarakat inklusi, karena pengalaman dari Kota Depok tersebut masyarakat sekolah dan media menciptakan sekat bagi anak korban kekerasan seksual. Kondisi demikian membuat sang anak menanggung beban ganda sebagai korban dalam masalah kekerasan berbasis gender yang ia alami.
Pengalaman kedua yakni terkait wacana formulasi kebijakan di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan dalam pengadaan tes keperawanan. Tes tersebut untuk merespons maraknya kasus siswi sekolah yang diduga melakukan praktik prostitusi. Diwacanakan rencana tes tersebut akan diajukan untuk APBD 2014. Hal ini sontak menjadi perhatian dan kontroversi publik. Pemenuhan hak anak korban kekerasan berbasis gender penting untuk mendapatkan perhatian dan fokus kita. Sensitivitas masyarakat patriaki kita masih rendah terhadap hal-hal yang bersifat inklusif.
Beban psikologis yang dibawa oleh sang anak menjadi sangat besar ketika lingkungan mulai memberlakukan sekat pada anak korban kekerasan seksual. Para perempuan yang telah menjadi korban kekerasan dapat menjadi semakin terpojokkan dalam sisi pelabelan. Budaya masyarakat ketika muncul masalah kekerasan berbasis gender bahwasanya letak kesalahan dan pihak penanggung akibat adalah perempuan.
Sikap pihak sekolah yang seakan memberikan lampu merah bagi siswa korban kekerasan berbasis gender untuk masuk dalam lingkungan sekolah membuat seorang anak tertekan secara psikologis untuk berafiliasi dalam lingkungan sekunder. Ketimpangan gender muncul lantaran stereotip pada anak perempuan korban kekerasan mengakibatkan diskriminasi, seperti halnya kalangan masyarakat Indonesia ada semacam dubble moral, jika perempuan yang melanggar batas kesopanan mereka akan dicela, tetapi jika yang melakukan adalah seorang laki-laki maka hanya dimaklumi saja (Irwan Abdullah, 1997).
Bukan Sekedar Branding
Membumikan Kota Layak Anak dan pencanangan Kota Inklusi menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Surakarta. Kota Surakarta yang tengah menuju Kota Layak Anak (KLA) dapat belajar dari pengalaman Kota Depok. Salah satu poin dalam Kota Layak Anak adalah adanya pencegahan pan penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Layak Anak. Kita dapat menggarisbawahi dalam masalah publik yang satu ini bahwasanya anak korban kekerasan seksual mendapati sekat ketika masuk ke lingkungan sekolahnya pasca ia mengalami kekerasan seksual. Ada amanat di tingkat Internasional yaitu education for all, semua anak berhak atas pendidikan tanpa diskiriminasi.
Kota Layak Anak harapannya tidak sekedar menjadi lips service dan branding image dari stakeholder penyedia dan penyelenggara pelayanan publik. Kota Layak Anak dikukuhkan sebagai upaya pemenuhan hak anak-anak atas bentuk-bentuk pelayanan publik dan kerangka besarnya adalah pemenuhan dari Hak Asasi Manusia. Mencapai tujuan kesetaraan akses dalam pendidikan dengan mengambil tindakan menghapus diskriminasi berdasarkan gender, suku, bahasa, agama, usia, atau bentuk diskriminasi lain, pada seluruh jenjang pendidikan dan jika diperlukan membuat aturan untuk mengatasi hal tersebut.
Pendidikan adalah salah satu jalan menjadikan individu sebagai agen perubahan, bukan sekedar penerima pasif program pemberdayaan. Merefleksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Sistem Pendidikan Indonesia harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, pasal 4 ayat(1) menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kondisi anak-anak korban kekerasan berbasis gender perlu didorong untuk menikmati peningkatan kapasitas pengetahuannya lewat pendidikan formal dan informal, khususnya pada pendidikan wajib 9 tahun dan di beberapa wilayah telah mencanakan pendidiakan wajib 12 tahun. Negara telah menjamin pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, alasan korban ganda kekerasan berbasis gender untuk mengakses pendidikan selayaknya sudah tidak ada lagi di waktu yang akan datang.
Menjadi angin segar bagi kita semua, bahwa dalam perumusan Solo Kota Inklusi pemenuhan hak anak dalam pendidikan inklusif tidak terbatas pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan kategori disabilitas dan korban NAPZA, akan tetapi juga tengah berupaya memperjuangan hak anak dengan HIV AIDS dan anak korban kekerasan seksual berbasis gender. Rekomendasi bagi persoalan yang memberikan sekat bagi anak perempuan korban kekerasan seksual dan/atau anak perempuan hamil adalah tetap memperhatikan pemenuhan hak pendidikan mereka. Peran serta masyarakat sekolah dan orang tua sangat penting dalam mewujudkan sebuah kota inklusi. Sensivitas mereka harus dapat terbangun mulai dari sekarang, disaat pemerintah tengah bekerja kerja menggodok formulasi kebijakan pendidikan inklusi ini.