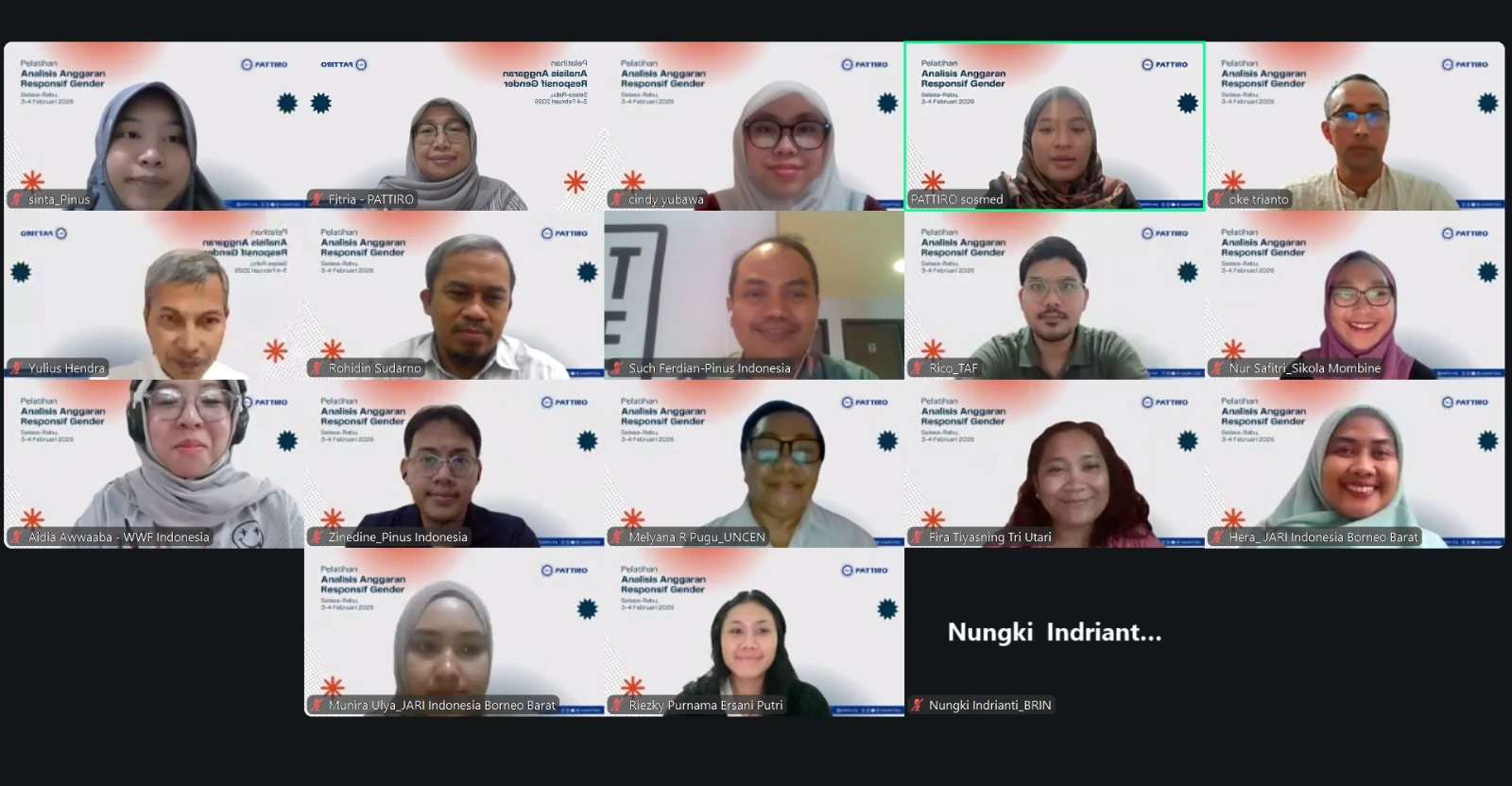Oleh: Robert Endi Jaweng, Jakarta | Opini | Selasa, 11 Maret 2014
Churchill Mining Plc Corp. yang terdaftar di London telah mengajukan sengketa pertambangannya dengan pemerintah Indonesia ke hadapan International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang berbasis di Washington, menuntut kompensasi lebih dari US$1 miliar atas kerugian yang disebabkan oleh pencabutan izin pertambangannya oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur.
Pemerintah tampaknya optimis memenangkan kasus itu karena Churchill tidak terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan tidak memiliki izin operasi sebagai pemilik usaha pertambangan di Indonesia.
Sambil menunggu proses arbitrase, kasus ini menghadirkan dimensi lain dalam konteks pengelolaan otonomi daerah kita. Pembagian kekuasaan melalui kebijakan desentralisasi tahun 2001 tidak hanya berdampak pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga pada sektor bisnis terkait dengan risiko politik dan ketidakpastian peraturan investasi.
Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang saat ini sedang dibahas di DPR harus menjadi pendorong perbaikan kerangka kebijakan, yaitu menjamin kejelasan pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antar entitas pemerintahan serta sebagai kepastian usaha di daerah.
Harus diakui, dibandingkan sektor lain, desentralisasi di sektor pertambangan (di luar migas) sangat drastis. Di sektor ekstraktif ini, pemerintah provinsi dan kabupaten diberi kewenangan untuk menerbitkan Hak Cipta Pertambangan (KP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan.
Perubahan mendasar dari sistem kontrak karya ke rezim perizinan berada di tangan pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan besar terhadap investor, dalam dan luar negeri.
Berdasarkan dampak putusan MK atas uji materil yang disampaikan Bupati Kutai Timur Isran Noor pada akhir 2012, kewenangan menetapkan wilayah pertambangan (WP), wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah cakupan dan batas wilayah IUP, yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat, berada di tangan pemerintah daerah.
Konstruksi terdesentralisasi seperti itu berdampak positif. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang lebih besar terhadap investor dan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya lokal. Diharapkan proses perizinan dapat dikelola lebih efektif karena rentang kendali pemegang kewenangan di lokasi usaha berkurang. Lebih jauh lagi, manfaat nyata yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam strategis tersebut kini semakin jelas dan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat.
Namun, pada tataran kebijakan, desentralisasi yang berjalan bebas tersebut memiliki masalah serius yang mempengaruhi implementasinya.
Pertama, perubahan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, yang dulu berdasarkan jenis atau kategori bahan galian yang digali menjadi berdasarkan luasan konsesi pertambangan, belum menjamin efisiensi atau akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kedua, model seperti itu mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan pemerintah pusat terhadap penanaman modal asing karena tingkat kewenangannya didasarkan pada wilayah operasi. Pemerintah daerah berperan sebagai pihak yang berurusan dengan investor asing, lintas batas, dan sebagai wakil negara untuk berunding dengan pihak ketiga (perusahaan asing).
Pembangunan ini semakin bermasalah karena lemahnya kontrol pemerintah pusat. Keseimbangan peran bisa saja terjadi jika pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah pertambangan. Pemerintah daerah hanya dapat menerbitkan IUP berdasarkan wilayah pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat kini lebih sulit melakukan kontrol karena semua proses mulai dari penetapan tahap WP hingga penerbitan IUP dipegang dan dikontrol oleh pemerintah daerah.
Ketiga, persoalan yang lebih serius terjadi di ranah kewenangan provinsi. Model pembagian kewenangan perizinan usaha berdasarkan luas wilayah konsesi pertambangan telah mengakibatkan terjadinya beberapa kecurangan di lapangan: Konsesi pemegang izin pertambangan yang melampaui kabupaten atau kabupaten sengaja dipecah dan dilokalkan di bawah yurisdiksi beberapa pemerintahan kabupaten sehingga dengan demikian, izin usaha atau izin pertambangan tersebut menjadi tanggung jawab di tingkat kabupaten.
Tidak mengherankan jika terjadi konflik antara gubernur provinsi yang menganggap wilayah pertambangan melampaui beberapa kabupaten dan bupati atau bupati yang dengan sengaja membagi wilayah pertambangan yang lebih besar menjadi beberapa konsesi pertambangan yang lebih kecil sehingga masing-masing konsesi berada dalam satu kabupaten atau kabupaten.
Di tingkat lapangan, masalah krusial terkait kualitas tata kelola telah menambah kompleksitas sektor ini. Ada kesenjangan yang lebar antara otoritas administratif yang besar dengan kapasitas dan integritas kelembagaan. Praktik penambangan yang baik menjadi pengecualian daripada aturannya. Tidak ada manajemen yang baik; melainkan salah urus: Dari 10.556 izin pertambangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, 5.940 izin belum diverifikasi. Praktek-praktek buruk yang menyebabkan kerusakan lingkungan, penyelewengan kekuasaan desentralisasi dan korupsi telah merajalela.
Untuk mengatasi masalah tersebut, kewenangan perizinan usaha pertambangan harus dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah harus diubah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah harus ditingkatkan dan pemerintah pusat harus memiliki kontrol yang lebih luas dan efektif terhadap pemerintah daerah.
Hal ini semakin penting dan mendesak karena kewenangan penetapan wilayah pertambangan dan pemberian IUP kini dipegang oleh pemerintah daerah.